

“Atlantis
The Lost Continents Finally Found”. Dimana ditemukannya ? Secara tegas
dinyatakannya bahwa lokasi Atlantis yang hilang sejak kira-kira 11.600
tahun yang lalu itu adalah di Indonesia (?!). Selama ini, benua yang
diceritakan Plato 2.500 tahun yang lalu itu adalah benua yang dihuni
oleh bangsa Atlantis yang memiliki peradaban yang sangat tinggi dengan
alamnya yang sangat kaya, yang kemudian hilang tenggelam ke dasar laut
oleh bencana banjir dan gempa bumi sebagai hukuman dari yang Kuasa.
Kisah Atlantis ini dibahas dari masa ke masa, dan upaya penelusuran
terus pula dilakukan guna menemukan sisa-sisa peradaban tinggi yang
telah dicapai oleh bangsa Atlantis itu.
Pencarian dilakukan di Samudera Atlantik, Laut
Tengah, Karibia, sampai ke kutub Utara. Pencarian ini sama sekali tidak
ada hasilnya, sehingga sebagian orang beranggapan bahwa yang
diceritakan Plato itu hanyalah negeri dongeng semata. Profesor Santos
yang ahli Fisika Nuklir ini menyatakan bahwa Atlantis tidak pernah
ditemukan karena dicari di tempat yang salah. Lokasi yang benar secara
menyakinkan adalah Indonesia, katanya..
Prof. Santos mengatakan bahwa dia sudah meneliti kemungkinan lokasi
Atlantis selama 29 tahun terakhir ini. Ilmu yang digunakan Santos dalam
menelusur lokasi Atlantis ini adalah ilmu Geologi, Astronomi,
Paleontologi, Archeologi, Linguistik, Ethnologi, dan Comparative
Mythology. Buku Santos sewaktu ditanyakan ke ‘Amazon.com’ seminggu yang
lalu ternyata habis tidak bersisa. Bukunya ini terlink ke 400 buah
sites di Internet, dan websitenya sendiri menurut Santos selama ini
telah dikunjungi sebanyak 2.500.000 visitors. Ini adalah iklan gratis
untuk mengenalkan Indonesia secara efektif ke dunia luar, yang tidak
memerlukan dana 1 sen pun dari Pemerintah RI.
Plato pernah menulis tentang Atlantis pada masa dimana Yunani masih
menjadi pusat kebudayaan Dunia Barat (Western World). Sampai saat ini
belum dapat dideteksi apakah sang ahli falsafah ini hanya menceritakan
sebuah mitos, moral fable, science fiction, ataukah sebenarnya dia
menceritakan sebuah kisah sejarah. Ataukah pula dia menjelaskan sebuah
fakta secara jujur bahwa Atlantis adalah sebuah realitas absolut ?
Plato bercerita bahwa Atlantis adalah sebuah negara makmur
dengan emas, batuan mulia, dan ‘mother of all civilazation’ dengan
kerajaan berukuran benua yang menguasai pelayaran, perdagangan,
menguasai ilmu metalurgi, memiliki jaringan irigasi, dengan kehidupan
berkesenian, tarian, teater, musik, dan olahraga.
Warga Atlantis yang semula merupakan orang-orang terhormat
dan kaya, kemudian berubah menjadi ambisius. Yang kuasa kemudian
menghukum mereka dengan mendatangkan banjir, letusan gunung berapi, dan
gempa bumi yang sedemikian dahsyatnya sehingga menenggelamkan seluruh
benua itu.
Kisah-kisah sejenis atau mirip kisah Atlantis ini yang berakhir dengan
bencana banjir dan gempa bumi, ternyata juga ditemui dalam kisah-kisah
sakral tradisional di berbagai bagian dunia, yang diceritakan dalam
bahasa setempat. Menurut Santos, ukuran waktu yang diberikan Plato
11.600 tahun BP (Before Present), secara tepat bersamaan dengan
berakhirnya Zaman Es Pleistocene, yang juga menimbulkan bencana banjir
dan gempa yang sangat hebat.
Bencana ini menyebabkan punahnya 70% dari species mamalia
yang hidup saat itu, termasuk kemungkinan juga dua species manusia :
Neandertal dan Cro-Magnon.
Sebelum terjadinya bencana banjir itu, pulau Sumatera, pulau Jawa,
Kalimantan dan Nusa Tenggara masih menyatu dengan semenanjung Malaysia
dan benua Asia.
Posisi Indonesia terletak pada 3 lempeng tektonis yang
saling menekan, yang menimbulkan sederetan gunung berapi mulai dari
Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan terus ke Utara sampai ke Filipina
yang merupakan bagian dari ‘Ring of Fire’.
Gunung utama yang disebutkan oleh Santos, yang memegang
peranan penting dalam bencana ini adalah Gunung Krakatau dan ‘sebuah
gunung lain’ (kemungkinan Gunung Toba). Gunung lain yang disebut-sebut
(dalam kaitannya dengan kisah-kisah mytologi adalah Gunung Semeru,
Gunung Agung, dan Gunung Rinjani.
Bencana alam beruntun ini menurut Santos dimulai dengan ledakan dahsyat
gunung Krakatau, yang memusnahkan seluruh gunung itu sendiri, dan
membentuk sebuah kaldera besar yaitu selat Sunda yang jadinya
memisahkan pulau Sumatera dan Jawa.
Letusan ini menimbulkan tsunami dengan gelombang laut yang sangat
tinggi, yang kemudian menutupi dataran-dataran rendah diantara Sumatera
dengan Semenanjung Malaysia, diantara Jawa dan Kalimantan, dan antara
Sumatera dan Kalimantan. Abu hasil letusan gunung Krakatau yang berupa
‘fly-ash’ naik tinggi ke udara dan ditiup angin ke seluruh bagian dunia
yang pada masa itu sebagian besar masih ditutup es (Zaman Es
Pleistocene) .
Abu ini kemudian turun dan menutupi lapisan es. Akibat adanya lapisan
abu, es kemudian mencair sebagai akibat panas matahari yang diserap
oleh lapisan abu tersebut.
Gletser di kutub Utara dan Eropah kemudian meleleh dan mengalir ke
seluruh bagian bumi yang rendah, termasuk Indonesia. Banjir akibat
tsunami dan lelehan es inilah yang menyebabkan air laut naik sekitar
130 meter diatas dataran rendah Indonesia. Dataran rendah di Indonesia
tenggelam dibawah muka laut, dan yang tinggal adalah dataran tinggi dan
puncak-puncak gunung berapi.
Tekanan air yang besar ini menimbulkan tarikan dan tekanan yang hebat
pada lempeng-lempeng benua, yang selanjutnya menimbulkan
letusan-letusan gunung berapi selanjutnya dan gempa bumi yang dahsyat.
Akibatnya adalah berakhirnya Zaman Es Pleitocene secara dramatis.
Dalam bukunya Plato menyebutkan bahwa Atlantis adalah
negara makmur yang bermandi matahari sepanjang waktu. Padahal zaman
pada waktu itu adalah Zaman Es, dimana temperatur bumi secara
menyeluruh adalah kira-kira 15 derajat Celcius lebih dingin dari
sekarang.
Lokasi yang bermandi sinar matahari pada waktu itu hanyalah Indonesia yang memang terletak di katulistiwa.
Plato juga menyebutkan bahwa luas benua Atlantis yang hilang itu
“….lebih besar dari Lybia (Afrika Utara) dan Asia Kecil digabung jadi
satu…”. Luas ini persis sama dengan luas kawasan Indonesia ditambah
dengan luas Laut China Selatan.
Menurut Profesor Santos, para ahli yang umumnya berasal dari Barat,
berkeyakinan teguh bahwa peradaban manusia berasal dari dunia mereka.
Tapi realitas menunjukkan bahwa Atlantis berada di bawah perairan
Indonesia dan bukan di tempat lain.
Walau dikisahkan dalam bahasa mereka masing-masing, ternyata
istilah-istilah yang digunakan banyak yang merujuk ke hal atau kejadian
yang sama.
Santos menyimpulkan bahwa penduduk Atlantis terdiri dari beberapa
suku/etnis, dimana 2 buah suku terbesar adalah Aryan dan Dravidas.
Semua suku bangsa ini sebelumya berasal dari Afrika 3 juta tahun yang
lalu, yang kemudian menyebar ke seluruh Eurasia dan ke Timur sampai
Auatralia lebih kurang 1 juta tahun yang lalu. Di Indonesia mereka
menemukan kondisi alam yang ideal untuk berkembang, yang menumbuhkan
pengetahuan tentang pertanian serta peradaban secara menyeluruh. Ini
terjadi pada zaman Pleistocene.
Pada Zaman Es itu, Atlantis adalah surga tropis dengan padang-padang
yang indah, gunung, batu-batu mulia, metal berbagai jenis, parfum,
sungai, danau, saluran irigasi, pertanian yang sangat produktif, istana
emas dengan dinding-dinding perak, gajah, dan bermacam hewan liar
lainnya. Menurut Santos, hanya Indonesialah yang sekaya ini (!). Ketika
bencana yang diceritakan diatas terjadi, dimana air laut naik setinggi
kira-kira 130 meter, penduduk Atlantis yang selamat terpaksa keluar
dan pindah ke India, Asia Tenggara, China, Polynesia, dan Amerika.
Suku Aryan yang bermigrasi ke India mula-mula pindah dan menetap di
lembah Indus. . Karena glacier Himalaya juga mencair dan menimbulkan
banjir di lembah Indus, mereka bermigrasi lebih lanjut ke Mesir,
Mesopotamia, Palestin, Afrika Utara, dan Asia Utara.
Di tempat-tempat baru ini mereka kemudian berupaya mengembangkan kembali budaya Atlantis yang merupakan akar budaya mereka.
Catatan terbaik dari tenggelamnya benua Atlantis ini dicatat di India
melalui tradisi-tradisi cuci di daerah seperti Lanka, Kumari Kandan,
Tripura, dan lain-lain. Mereka adalah pewaris dari budaya yang
tenggelam tersebut.
Suku Dravidas yang berkulit lebih gelap tetap tinggal di Indonesia.
Migrasi besar-besaran ini dapat menjelaskan timbulnya secara tiba-tiba
atau seketika teknologi maju seperti pertanian, pengolahan batu mulia,
metalurgi, agama, dan diatas semuanya adalah bahasa dan abjad di
seluruh dunia selama masa yang disebut Neolithic Revolution.
Bahasa-bahasa dapat ditelusur berasal dari Sansekerta dan Dravida.
Karenanya bahasa-bahasa di dunia sangat maju dipandang dari gramatika
dan semantik. Contohnya adalah abjad. Semua abjad menunjukkan adanya
“sidik jari” dari India yang pada masa itu merupakan bagian yang
integral dari Indonesia.
Dari Indonesialah lahir bibit-bibit peradaban yang kemudian berkembang
menjadi budaya lembah Indus, Mesir, Mesopotamia, Hatti, Junani, Minoan,
Crete, Roma, Inka, Maya, Aztek, dan lain-lain. Budaya-budaya ini
mengenal mitos yang sangat mirip. Nama Atlantis diberbagai suku bangsa
disebut sebagai Tala, Attala, Patala, Talatala, Thule, Tollan, Aztlan,
Tluloc, dan lain-lain.
Itulah ringkasan teori Profesor Santos yang ingin membuktikan bahwa
benua atlantis yang hilang itu sebenarnya berada di Indonesia.
Bukti-bukti yang menguatkan Indonesia sebagai Atlantis, dibandingkan
dengan lokasi alternative lainnya disimpulkan Profesor Santos dalam
suatu matrix yang disebutnya sebagai ‘Checklist’.
Terlepas dari benar atau tidaknya teori ini, atau dapat dibuktikannya
atau tidak kelak keberadaan Atlantis di bawah laut di Indonesia, teori
Profesor Santos ini sampai saat ini ternyata mampu menarik perhatian
orang-orang luar ke Indonesia. Teori ini juga disusun dengan
argumentasi atau hujjah yang cukup jelas.
Kalau ada yang beranggapan bahwa kualitas bangsa Indonesia sekarang
sama sekali “tidak meyakinkan” untuk dapat dikatakan sebagai nenek
moyang dari bangsa-bangsa maju yang diturunkannya itu, maka ini adalah
suatu proses maju atau mundurnya peradaban yang memakan waktu lebih
dari sepuluh ribu tahun. Contoh kecilnya, ya perbandingan yang sangat
populer tentang orang Malaysia dan Indonesia; dimana 30 tahunan yang
lalu mereka masih belajar dari kita, dan sekarang mereka relatif berada
di depan kita.
Allah SWT juga berfirman bahwa nasib manusia ini memang dipergilirkan.
Yang mulia suatu saat akan menjadi hina, dan sebaliknya. Profesor
Santos akan terus melakukan penelitian lapangan lebih lanjut guna
membuktikan teorinya. Kemajuan teknologi masa kini seperti satelit yang
mampu memetakan dasar lautan, kapal selam mini untuk penelitian
(sebagaimana yang digunakan untuk menemukan kapal ‘Titanic’), dan
beragam peralatan canggih lainnya diharapkannya akan mampu membantu
mencari bukti-bukti pendukung yang kini diduga masih tersembunyi di
dasar laut di Indonesia.
Apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan bangsa Indonesia ?
Bagaimana pula pakar Indonesia dari berbagai disiplin keilmuan
menanggapi teori yang sebenarnya “mengangkat” Indonesia ke posisi
sangat terhormat : sebagai asal usul peradaban bangsa-bangsa seluruh
dunia ini ?
Coba kita renungkan penyebab Atlantis dulu dihancurkan : penduduk
cerdas terhormat yang berubah menjadi ambisius serta berbagai kelakuan
buruk lainnya (mungkin ‘korupsi’ salah satunya). Nah, salah-salah
Indonesia sang “mantan Atlantis” ini bakal kena hukuman lagi nanti
kalau tidak mau berubah seperti yang ditampakkan bangsa ini secara
terang-terangan sekarang ini.
Demikian kutipan dari Catatan Bang Ferdy Dailami Firdaus tentang Teori
Santos secara ringkas. Bagi yang berminat untuk membaca lebih jelas,
dapat langsung ke website Profesor Arysio Nunes Dos Santos – Atlantis
The Lost Continent Finally Found http://www.atlan.org/
(badruttamamgaffas.blogspot.com)
 Candi
Cetho ini terletak di dusun Cetho Desa Gumeng Kecamatan Jenawi
Kabupaten Karangayar, terletak pada 1400m di atas permukaan air laut.
Dari Magetan tempat ini ditempuh dengan kendaraan pribadi selama 2 jam
perjalanan, melewati jalan tembus Cemoro Sewu yang siang itu terlihat
mulus dan tidak begitu ramai, maklum bukan hari libur. Awalnya saya
pikir bahwa Candi ini letaknya tidak jauh dari air Terjun Grojogan Sewu
Tawangmangu, ternyata perkiraan saya salah besar.
Candi
Cetho ini terletak di dusun Cetho Desa Gumeng Kecamatan Jenawi
Kabupaten Karangayar, terletak pada 1400m di atas permukaan air laut.
Dari Magetan tempat ini ditempuh dengan kendaraan pribadi selama 2 jam
perjalanan, melewati jalan tembus Cemoro Sewu yang siang itu terlihat
mulus dan tidak begitu ramai, maklum bukan hari libur. Awalnya saya
pikir bahwa Candi ini letaknya tidak jauh dari air Terjun Grojogan Sewu
Tawangmangu, ternyata perkiraan saya salah besar. Semakin
jauh, jalan semakin menanjak, mobil mulai memasuki perkebunan teh, yang
siang itu terlihat sangat indah. Mobil meliuk-liuk membelah perkebunan
teh, melingkari bukit-bukit hijau, kadang membelok tajam dan harus mampu
melewati tanjakan-tanjakan setan yang luar biasa menantang, untung
skill mengemudi teman saya bisa diandalkan. Sepanjang mata memandang
hanya “hijau” yang kami temukan. Satu putaran lagi, kata teman saya,
candinya ada di puncak bukit itu, begitu katanya sambil menunjuk sebuah
bukit di depan sana. Oh God…Lindungilah Kami, jalannya kecil dan ada
sebagian ruas yang tertimbun tanah karena longsoran dari bukit
diatasnya.
Semakin
jauh, jalan semakin menanjak, mobil mulai memasuki perkebunan teh, yang
siang itu terlihat sangat indah. Mobil meliuk-liuk membelah perkebunan
teh, melingkari bukit-bukit hijau, kadang membelok tajam dan harus mampu
melewati tanjakan-tanjakan setan yang luar biasa menantang, untung
skill mengemudi teman saya bisa diandalkan. Sepanjang mata memandang
hanya “hijau” yang kami temukan. Satu putaran lagi, kata teman saya,
candinya ada di puncak bukit itu, begitu katanya sambil menunjuk sebuah
bukit di depan sana. Oh God…Lindungilah Kami, jalannya kecil dan ada
sebagian ruas yang tertimbun tanah karena longsoran dari bukit
diatasnya. Dengan
perjuangan, akhirnya sampai juga di sana, memasuki dusun Cetho mobil
membelok ke kiri, dan salah satu gapura candi terlihat begitu menantang.
Tiket masuk ke candi seharga Rp 4.000,00 per orang.
Dengan
perjuangan, akhirnya sampai juga di sana, memasuki dusun Cetho mobil
membelok ke kiri, dan salah satu gapura candi terlihat begitu menantang.
Tiket masuk ke candi seharga Rp 4.000,00 per orang. Pada
aras selanjutnya dapat ditemui jajaran batu pada dua dataran
bersebelahan yang memuat relief cuplikan kisah Sudhamala, seperti yang
terdapat pula di Candi Sukuh. Dua aras berikutnya memuat
bangunan-bangunan pendapa yang mengapit jalan masuk candi. Sampai saat
ini pendapa-pendapa tersebut digunakan sebagai tempat pelangsungan
upacara-upacara keagamaan. Pada aras kedelapan terdapat arca phallus
(disebut “kuntobimo”) di sisi utara dan arca Sang Prabu Brawijaya V
dalam wujud mahadewa. Aras terakhir (kesembilan) adalah aras tertinggi
sebagai tempat pemanjatan doa. Di sini terdapat bangunan batu berbentuk
kubus.
Pada
aras selanjutnya dapat ditemui jajaran batu pada dua dataran
bersebelahan yang memuat relief cuplikan kisah Sudhamala, seperti yang
terdapat pula di Candi Sukuh. Dua aras berikutnya memuat
bangunan-bangunan pendapa yang mengapit jalan masuk candi. Sampai saat
ini pendapa-pendapa tersebut digunakan sebagai tempat pelangsungan
upacara-upacara keagamaan. Pada aras kedelapan terdapat arca phallus
(disebut “kuntobimo”) di sisi utara dan arca Sang Prabu Brawijaya V
dalam wujud mahadewa. Aras terakhir (kesembilan) adalah aras tertinggi
sebagai tempat pemanjatan doa. Di sini terdapat bangunan batu berbentuk
kubus.
















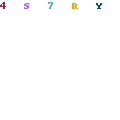




 Yang
paling menarik yang bisa anda lakukan didesa ini adalah, meneropong dan
melihat aktifitas burung kuntul putih dari gardu pandang, waktu yang
pas jika anda ingin melihat burung kuntul putih pada waktu pagi dan
sore, saat pagi burung kuntul ini melakukkan aktivitas dengan
berterbangan keluar desa dengan bergerombol, sedangkan waktu sore hari
burung kuntul putih akan kembali pulang kedesa ketingan ini, Selain itu
saat bulan purnama anda akan melihat tingkah laku burung kuntul yang
unik, burung kuntul putih ini akan berterbangan dari sore hingga malam
diatas desa ketingan, desa ketingan memang sudah menjadi habitat dan
rumah bagi burung kuntul putih karena keadaan desa yang masih terdapat
pohon- pohon yang menjulang tinggi dan rimbun yang bisa digunakan untuk
bersarang, tentunya ini akan menjadi hal yang sangat menarik untuk anda
lihat bersama keluarga dan anak- anak anda. Selain kegiatan meneropong
burung kuntul, tentunya kegiatan bertani dan melihat pertunjukan seni
desa menjadi sajian utama dari desa wisata ketingan ini.
Yang
paling menarik yang bisa anda lakukan didesa ini adalah, meneropong dan
melihat aktifitas burung kuntul putih dari gardu pandang, waktu yang
pas jika anda ingin melihat burung kuntul putih pada waktu pagi dan
sore, saat pagi burung kuntul ini melakukkan aktivitas dengan
berterbangan keluar desa dengan bergerombol, sedangkan waktu sore hari
burung kuntul putih akan kembali pulang kedesa ketingan ini, Selain itu
saat bulan purnama anda akan melihat tingkah laku burung kuntul yang
unik, burung kuntul putih ini akan berterbangan dari sore hingga malam
diatas desa ketingan, desa ketingan memang sudah menjadi habitat dan
rumah bagi burung kuntul putih karena keadaan desa yang masih terdapat
pohon- pohon yang menjulang tinggi dan rimbun yang bisa digunakan untuk
bersarang, tentunya ini akan menjadi hal yang sangat menarik untuk anda
lihat bersama keluarga dan anak- anak anda. Selain kegiatan meneropong
burung kuntul, tentunya kegiatan bertani dan melihat pertunjukan seni
desa menjadi sajian utama dari desa wisata ketingan ini.

























